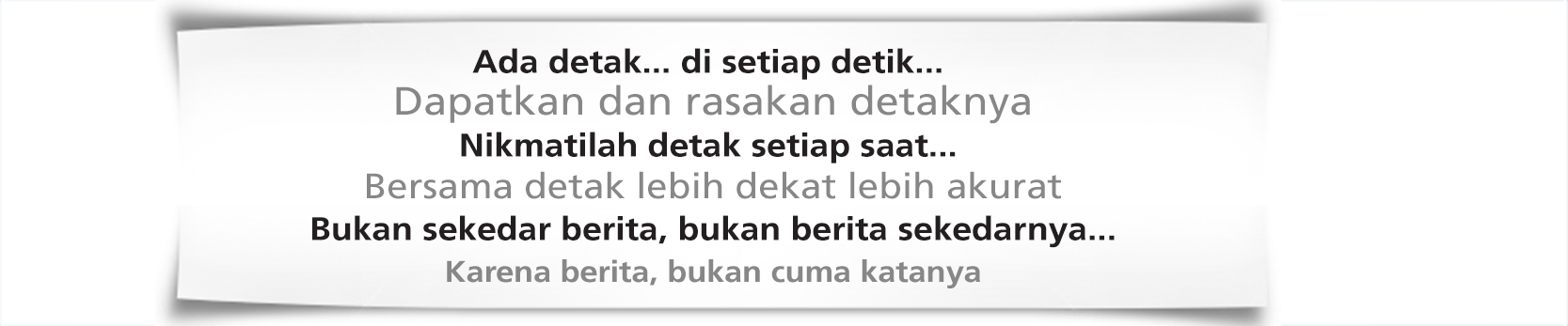Kehambaran acapkali diibaratkan sebagai ‘sayur kurang garam’. Hal ini menegaskan akan urgensi garam di dalam dunia kuliner.
Sesungguhnya, garam bukan hanya bermanfaat bagi kuliner, melainkan juga untuk kefaedahan-kefaedahan lain. Mengingat bahwa dimanapun dan kapanpun garam senantiasa dibutuhkan, maka pada masa lalu, Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan garam sebagai salah satu diantara “sembilan bahan kebutuhan pokok”.
Demikian pula, berdasarkan arti strategis dari garam tersebut, maka penguasa ‘Kolonial Sisipan” Inggris, Th. S. Raffles (1811-1816), tepatnya 15 Oktober 1913, mengeluarkan peraturan menghapusakan sistem ‘penyerahan wajib (contingenten)’ serta sistem ‘penyewaan produksi dan perdagangan garam yang dilakukan oleh para pachter (pemborong)’.
Sebagai gantinya, Raffles tempatkan industri garam sebagai ‘perusahaan negara’, dengan menerapkan sistem free labor (vrje arbeid)’.
Urusan perdagangan dan distribusi garam dikelola oleh perusahaan negara. Aturan ini memberikan gambaran mengenai kebijakan ekonominya, yang salah sebuah diantaranya adalah mengadakan monopoli garam dan minuman keras.
Pada tahap ini, sebenarnya produksi garam telah mulai masuk ke dalam ketegori upaya pengindustrian modern, meski praktik ini tidak berlangsung lama, karena segera digantikan setelah kedatangan kembali Belanda.
Pemerintah Kolonial Belanda cenderung mengeluarkan kebijakan, yang ingin menguatkan posisi pemerintah dalam industri.
Pada tahun 1818 misalnya, dilaksanakan kontrol terhadap produksi dan perdagangan garam di daerah-daerah, yang dikuasakan kepada para residen. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, lataran banyak kepentingan pejabat lokal yang turut menyebabkan pemasukan pemerintah dari sektor garam menjadi berkurang.
Kedatipun upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hinda-Balanda ini cenderang memonopolisasi garam, akan tetapi dalam praktiknya tidak terdapat kebulatan mengenai monopoli garam. Ironinya, paktik itu tak berjalan dengan sama memuaskan di semua tempat. Masa kelebihan dan sebaliknya kekuragan garam terjadi silih ganti.
Pada sisi lain, pejabat-pejabat korup mengahalangi tujuan dari itu. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pembatasan produksi garam, yang mengakibatkan stok garam di gudang-gudang garam pemerintah berlebih. Akibatnya. terjadilah krisis garam di Hindia-Belanda pada tahun 1851-1861.
Menyikapi krisis garam tersebut, Pemerintah Hindia-Belanda terpaksa menghentikan produksi bahkan menutup ladang-ladang garam di beberapa daerah, sehingga produsen-produsen garam yang hidupnya semata bergantung kepada produksi garam praktis kehilangan pencaharian.
Banyak orang menjadi tidak kerja, malahan beberapa lainnya melakukan tindak kejahatan, atau sebagian petani penggarap garam yang masih tradisional menjalankan produksi-produksi gelap. Untuk itulah maka pada dekade 1860-an dan 1870-an muncul gagasan untuk ‘membebaskan produksi dan perdagangan garam’.
Namun, gagasan ini dipertimbangkan secara serius dan akhirnya dibuang jauh-jauh sebab takut pendapatan negara menjadi berkurang. Pada sisi lain, distribusi produk tidak merata dengan alasan kesenjangan harga. Menghadapi carut-marut perindustrian garam itu, untuk mengakhiri berbagai ketidak pastian dan praktik yang bermacam-macam, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang telah disebut di atas.
Pada akhiranya, Pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan ‘Sistem Monopoli Garam (Bepalingen tot Verzekering van het Zoutmonopolie)’, yang diresmikan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Dengan kebijakan ini, maka ketentuan yang dibuat Komisaris Jendral Du Boys tahun 1829 – pasca Perang Diponegoro (1825-1830) – yakni menyewakan pengelolaan garam terhadap pihak swasta (patikelir) guna menutup defisit keuangan VOC berakhir sudah.
Sebenarnya, monopoli garam ini merupakan pengulangan terhadap apa yang pernah diterapkan Raffles tujuh dasawarsa terdahulu.
Lewat peraturan itu, Pemerintah Hindia-Belanda melakukan memonopoli produksi sampai perdagangan garam, dengan tujuan untuk tingkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam.
Peraturan itu juga menjadi tonggak awal bagi pendefinisian produksi garam sebagai suatu industri yang modern. Di kemudian hari, aturan itu secara bertutut-turut disempurnakan. Antara lain tahun 1921 dikeluarkan Staatsblad No. 454, tahun 1923 (Staatsblad No. 20), tahun 1930 (Staatsblad No. 119), dan tahun 1931 Staatsblad No. 168 dan 191. Tonggak penting lainnya bagi transformasi produksi garam menjadi industri modern adalah pada tahun 1921, ketika pemerintah Hindia-Belanda mendirikan perusahaan garam dengan nama “Jawatan Regie Garam’.
Selanjutnya, pada tahun 1937 diubah menjadi ‘Jawatan Regie Garam dan Candu’. Keduanya itu merupakan cikal-bakal dari apa yang sekarang dinamai “PT. Garam Persero’
.
Kendatipun maksud dari kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam, namun tidak terelakan kebijakkan monopolisasi garam menghadapi ketiadakstabilan atau flukstuasi hasil produksii. Hal itu disebabkan beberapa factor. Misalnya, kenaikan hasil produksi garam di Bagan Siapi-api pada tahun 1904 dan1907, yang meningkat tidak cukup signifikan dari f 6.060 hanya menjadi f 15.360, sebab masih terdapat persaingan produksi.
Bahkan secara nasional pada tahun 1909 dan 1910 terjadi kelangkaan garam, sehingga mendorong pihak manajemen dari peraturan monopoli garam untuk menyempurnakan diri. Antara lain, pada tahun 1912 Perusahaan Garam di Hindia- Belanda membuka firma pelayarannya sendiri.
Di Kalianget, yakni salah sebuah sentra pengahasil garam, didirikan pabrik-pabil, perkantoranm perumahan pegawai berkebangsaan Eropa dan bandar baru. Dari bandar baru inilah kapal-kapal bermuatan garam berlayar ke seantero wilayah.
Sematara itu, di Bagan Siapi-api, produksi garam didistribusikan melalui ‘Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)’. Wal hasil, produksi garam dari tahun 1901 meningkat – meski pada tahun 1906 sempat menurun. Pada tahun 1930an, kerika secara global negera-negera dilanda ‘Depresi Ekonomi’, beberapa komoditi mengalami fluktuasi yang tajam, tidak terkecuali garam.
Untuk menghadapi itu, pada tahun 1936 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memperluas lahan-lahan garam berskala besar (3000 hektar) serta dengan tambak-tambak garam yang berskala kecil.
Sebelum penerapkan kebijakan ‘monopoli garam’ pada tahun 1882, pemaknaan terhadap industri garam belum dapat didefinisikan secara jelas, lantaran proses produksi hingga penjualan garam dilaksanakan layaknya pada proses tani.
Dalam kaitan itu, Kuntowijoyo (2002) menyatakan bahwa pada daerah-daerah yang secara ekologis berpotensi bila dijadikan sentra produksi garam, pekerjaan ini hanya dipoisiskan sebagai alternatif untuk pertanian. Artinya, ketika keadaan tidak menguntungkan bagi pertanian dan justru menuntungkan untuk produksi garam, maka dilakukan pekerjaan di bidang garam, atau sebaliknya.
Dalam konteks ini, proses produksi tani dan produksi garam dapat disamakan, yang keduanya belum dapat dimasukkan sebagai bagian aktifitas industri dalam arti modern, sehingga kegiatan ekonomi produksi garam sebagaimana itu tidaklah salah bila diketegorikan sebagai uapaya industri garam dalam pengertian sederhana.
Produksi garam pra-tahun 1882, kendati hanya merupakan pekerjaan alternatif, namun tak dapat dipungkiri bahwa terdapat motif ekonomik, yakni cari untung.
Hanya saja, masih belum mempunyai anasir industri modern, belum didukung modal besar, belum didasarkan pada asas kekeluargan maupun rancangan modern.
Kala itu produksi garam masih dilakukan dengan cara tradisional, atau setidaknya terdapat bias – percampuran antara (a) usaha mengindustrikan secara modern dengan (b) praktik produksi tradisional yang masih kental dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produksi garam belum tampak jelas sebagai suatu upaya pengindustrian dalam arti modern.
VOC terapkan peraturan ‘penyerahan wajib (contingenten)’ garam dari para patani penggarap dengan jumlah yang telah ditentukan. Aturan lainnya, para penggarap yang berada di bawah kekuasaan VOC dan ingin membuka tambak garam harus meminta izin dahulu.
Sistem yang dikembangkan oleh VOC ini pada perkembangannya jstru melahirkan kelas sosial baru, yaitu pachter (pemborong), yang merugikan para petani penggarap garam.
Kilas sejarah mengenai aktifitas industri garam diatas membuktikan bahwa industri garam bersfiat ‘dinamik’ dari masa ke masa. Dinamikanya tek terkucuali terjadi pada masa pra-Kolonial, yaitu pada Masa Hindu-Buddha dan Pertumbuhan-Perkembangan Islam.
Bagaimanakah gambaran mengenai keberadaan pergaraman pada Masa Hindu-Buddha, telaah ini akan menyingkapkannya, meski hanya sebatas pada Masa Majapahit, dengan contoh kasus khusus pada sub-area Lamongan Selatan. (*)
(M. Dwi Cahyono A. adalah Arkeolog dan Sejarawan Universitas Negeri Malang)