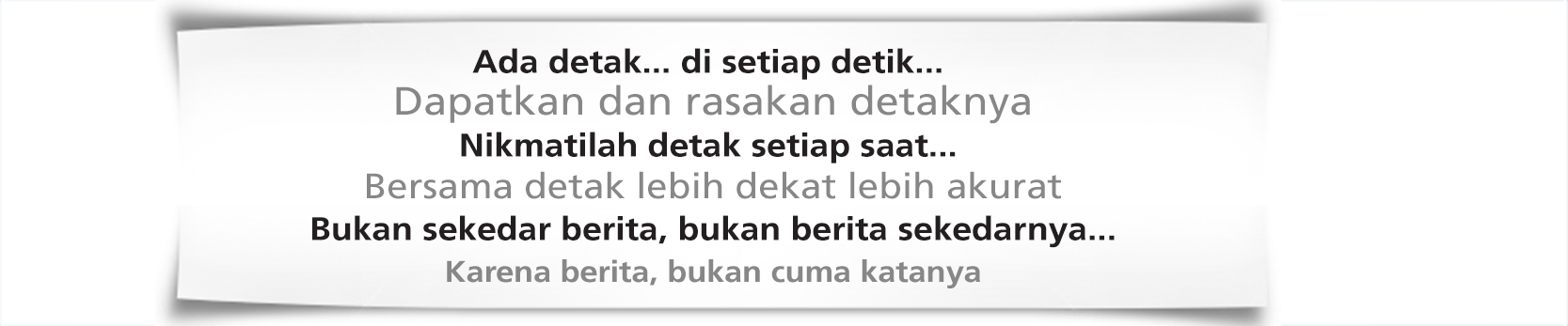HASIL Bahtsul Masâil Maudlū’iyah dalam Munas dan Konbes NU 2019 di Banjar, Jawa Barat, memicu polemik. Dari sekian isu penting, yang paling menyengat publik adalah hasil bahasan tema “Negara, Kewarganegaraan, Hukum Negara, dan Perdamaian.”
Ini bukan tema baru, tetapi kelanjutan dari visi kebangsaan NU. Tahun 1936, NU menyebut kawasan Nusantara sebagai Dârus Salâm. Tahun 1945, NU setuju NKRI berdasarkan Pancasila dan kemudian menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI dari pendudukan kolonial. Tahun 1953, NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dan menggelarinya dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlarūri bis Syaukah.
Tahun 1983-84, NU menegaskan NKRI final bagi perjuangan umat Islam. Tahun 1987, NU memperkenalkan trilogi ukhuwwah: Ukhuwwah Islâmiyah, Ukhuwwah Wathaniyah, Ukhuwwah Basyariyah/Insâniyah.
Produk penting ini perlu diingatkan, terutama kepada orang NU, yang mulai gemar menilai NU dengan kaca mata non-NU. Sejumlah grup WA isinya orang NU, tetapi menghujat produk Munas/Konbes NU 2019 terkait isu ini.
Terkait status non-Muslim, ada sebutan Kâfir Harby, Kâfir Dzimmy, Kâfir Mu’âhad, dan Kâfir Musta’min. Kâfir Harby merujuk ke orang kafir yang agresif karena itu harus diperangi. Kâfir Dzimmy merujuk ke orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang tunduk dan dilindungi dengan membayar jizyah (pajak). Kâfir Mu’âhad merujuk ke orang kafir yang dilindungi karena mengikat perjanjian. Kâfir Musta’min merujuk ke orang kafir yang datang ke negeri Islam yang minta perlindungan dan dilindungi.
Ini adalah kategori sosiologis-politis, bukan teologis. Orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW disebut kafir secara teologis. Tetapi, fikih jihad membagi mereka berdasarkan kategori sikap sosial dan politis. Semua haram darahnya, kecuali kâfir harby.
Kategori sosiologis-politis ini bias Negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Memang, teks kitab yang dikaji dan dirujuk di lingkungan NU, termasuk kelompok Islam lain, rata-rata disusun dalam konfigurasi politik dawlah Islâmiyah. Dalam konteks itu, orang Islam adalah pemain utama yang menguasai negara dan pemerintahan.
Status orang kafir tergantung sikapnya. Kalau dia agresif, dia harus dibunuh. Kalau tunduk dan bayar pajak, dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kalau minta perlindungan, harus dilindungi. Kalau mengikat perjanjian, wajib dilindungi selama tidak melanggar perjanjian.
Pertanyaannya, apakah kategorisasi ini tetap relevan dan bisa digunakan untuk menilai NKRI yang sejak semula telah ditetapkan sebagai bukan Negara Islam?
Musyâwirīn dalam forum Bahtsul Masâ’il sebagian masih terikat dengan teks harfiah kitab, karena itu tetap mengenakan idiom kafir untuk menghukumi status non-Muslim di Indonesia.
Perdebatan keras itu berujung kepada keluarnya idiom baru: Musâlimin. Istilah ini merujuk ke seluruh pihak yang terikat komitmen untuk saling menjaga dan melindungi. Konsepnya sudah jauh lebih egaliter. Semua pihak berkedudukan sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling menjaga dan melindungi.
Ketika konsep ini diplenokan, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroh, mengusulkan penggantian istilah Muwâthinin yaitu warga negara. Muwâthinin derivat dari kata wathan yang artinya bangsa.
Karena NKRI adalah bentuk dari Mu’âhadah Wathaniyah (konsensus kebangsaan), seluruh pihak, tanpa diskriminasi, adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Secara normatif, tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua berlaku prinisp keseteraan dan persamaan di muka hukum (equality before the law).
Keputusan ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Mu’min dan kafir itu tetap ada di ranah privat teologis masing-masing agama. Bagi orang Islam, non-Muslim itu kafir, begitu juga sebaliknya. Tetapi, idiom ini tidak berlaku di ranah publik (mu’âmalah wathaniyah).
Semua adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Ini persis seperti yang dilakukan Nabi ketika mendirikan Negara Madinah. Kaum Muslim dan Yahudi dengan beragam suku dan agamanya, di dalam naskah Piagam Madinah, semua disebut sebagai Ummatun Wâhidah.
Definisi ‘umat’ dalam Piagam Madinah bahkan jauh lebih inklusif daripada penggunaan sekarang, yang secara eksklusif hanya merujuk kepada umat Islam.
Umat dalam Piagam Madinah adalah warga negara yang berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi dan persekusi berbasis SARA. Prosekusi diberlakukan kepada seluruh pelanggar hukum, tidak peduli suku dan agamanya.
Adakah yang salah dengan keputusan ini? Sama sekali tidak! Ada pihak, yang dengan keputusan ini, ingin menambahkan bukti tentang penyimpangan NU di bawah kepimpinan KH. Said Aqil Siroj. NU, kata mereka, semakin menyimpang dari jalur para pendiri. Penilaian ini salah, totally wrong! Tahun 1936, Hadlratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari telah memimpin Muktamar di Banjarmasin yang memutuskan Nusantara sebagai kawasan damai (Dârus Salâm). Tidak berlaku hukum perang sejauh penguasa kolonial masih membolehkan umat Islam menjalankan syariat Islam, meskipun terbatas. Tahun 1945, Hadlratus Syeikh setuju Indonesia tidak menjadi Negara Islam, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila.
Di tahun yang sama, ketika kompeni berniat menduduki lagi negeri yang sudah diproklamirkan merdeka, Hadlratus Syeikh mencanangkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu. Tahun 1983-84, dalam kontinuum semangat yang sama, NU memutuskan NKRI final. Apa konsekuensi dari resepsi finalitas NKRI? Secara normatif, seluruh warga negara dalam NKRI berkedudukan sederajat. Tidak ada diskriminasi SARA. Orang Islam, meski mayoritas dari segi jumlah, tidak lantas kebal hukum atau ingin menjadi pemain utama.
Umat Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku sejauh tidak melanggar syariat. Tidak ada mukmin dan kafir di ranah publik NKRI. Yang ada adalah warga negara Indonesia, yang berbhinneka tunggal ika.
Sumber : Tim Bakhsul Masail Munas Konbes NU 2019.
Editor : A Adib