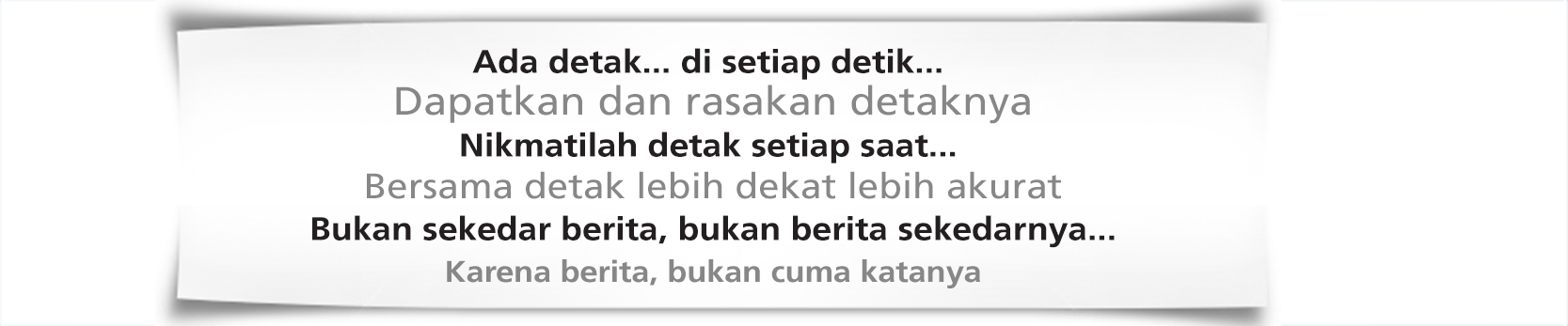Oleh A Adib Hambali (*)
FENOMENA perpolitikan daerah pascagelaran Pemilukada langsung adalag “pecah kongsi.”
Demikian para pengamat memberi label pada situasi politik bercerainya duet kepala daerah dan wakil kepala daerah itu.
Sepertinya terjadi setiap tahun sejak perhelatan Pilkada (kemudian Pemilukada). Setidaknya, pihak Kemendagri mencatat, sepanjang tahun 2010 dan 2011, dari 311 Pemilukada (Gubernur, Bupati, Walikota) hanya sekitar 6% yang tetap solid memangku jabatan hingga akhir kemudian kembali maju dalam posisi yang tetap sama untuk periode berikutnya.
Sisanya, berarti sekitar 94% berantakan, paling tidak di tahun penghujung masa jabatan mereka.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010-2014, Djohermansyah Djohan mensyinyalir, kinerja kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota tidak lepas dari gerak wakilnya. Namun, hampir 90 persen kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi di tengah jalan.
Secara normatif, hingga saat ini tidak ada satu pun ketentuan yang melarang pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah petahana bercerai.
Oleh sebab itu fenomena ini secara politik menjadi “halal”. Tetapi dari sisi etika, perilaku ini pantas dipersoalkan.
Yang paling mendasar adalah fenomena pecah kongsi ini mengisyaratkan, kontestasi Pemilukada benar-benar hanya menjadi ajang pertarungan memperebutkan kekuasaan dan kedudukan belaka.
Setidaknya, orientasi kekuasaan untuk kekuasaan jauh lebih hegemonik dalam cara pikir para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan, dibandingkan dengan orientasi kekuasaan untuk mewujudkan esensi makna kedaulatan rakyat, misalnya : keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
Perilaku ini jelas mengindikasikan betapa rendahnya akuntabilitas politik sang pemimpin terhadap amanah konstituen yang telah memberikan mandat kuasanya. Seperti sebuah ungkapan, “mereka tidak menyelesaikan apa yang telah mereka mulai”, yang justru mereka minta sendiri kepada rakyat.
Sementara itu, dalam konteks tatakelola pemerintah, fenomena ini juga berpotensi tak sehat bahkan kontraproduktif.
Sejumlah aspek tatakelola dan ekologi pemerintahan jelas bisa terganggu dengan situasi ini. Mulai dari soliditas birokrasi, stabilitas manajemen hingga aspek pelayanan publik yang seharusnya menjadi concern mereka sebagai kepala dan wakil kepala daerah.
Dalam konteks jangka menengah dan panjang, fenomena pecah kongsi yang semakin masif ini juga berpotensi buruk terhadap derajat kepercayaan politik masyrakat. Terutama pada segmen masyarakat yang kritis secara politik.
Djohan dalam diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Februari 2018 menyebutkan, calon kepala daerah dan wakil perlu memiliki visi dan misi sama.
Bukan sekadar visi misi yang diperlihatkan dan dijanjikan kepada rakyat untuk memenangkan pertarungan.
Banyak sekali yang berpasangan tetapi tidak ada chemistry-nya. Asal saja yang penting ada pasangan dan seolah-olah sama visi misinya. Kalau seperti itu selamat datang “pecah kongsi.”
Jika serius membangun daerah, calon kepala daerah dan wakil, perlu serius pula mempersiapkan hal tersebut.
Jadi, kepala daerah dan wakil bisa benar-benar bersinergi untuk membangun daerah. Tidak hanya menggebu-gebu waktu berkampanye
Kekompakan pasangan bupati dan wakil bupati dalam memimpin daerah kerap tidak bertahan lama. Kemesraan antara keduanya biasanya hanya bertahan selama enam bulan pertama pasca memenangkan pilkada.
Di banyak daerah, setelah satu tahun pemerintahan, konflik antara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sudah memanas. Bahkan, biasanya masing masing sudah menyusun kekuatan untuk melawan bupati di Pilkada selanjut.
Misal dengan membangun kekuatan pendukung, penguatan finansial, bahkan menyingkirkan mereka yang diperkirakan bukan pendukung. Apalagi jika sejak awal sudah menyatakan akan menjadi petahana. (*)
Penulis: Redaktur senior Detakpos