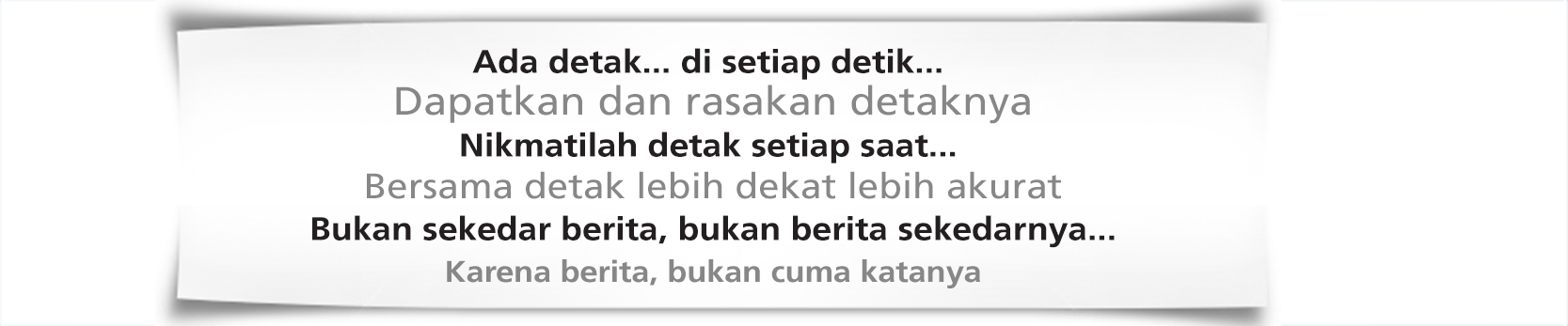Oleh A Adib Hambali (*
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden RI periode 2019-2024.
Meski baru akan dilantik Oktober 2019, Presiden mengaku sudah memilikial gambaran mengenai nama-nama dan komposisi kabinet periode mendatang.
Mantan wali kota Solo ini pun memastikan kabinetnya berasal dari latar belakang partai politik (parpol) dan profesional.
“Ya kira-kira 60:40 atau 50:50, kira-kira itu,” kata Presiden. (Detakpos, 12/7).
Parpol koalisi pun sudah ramai meminta jatah kursi kabinet. Bahkan sudah mematok meminta 9-10 menteri. “Mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan enggak apa-apa. Wong minta saja,”kata Presiden.
Sebanyak Sembilan parpol mengantarkan Jokowi ke Istana Negara untuk kali kedua. Memiliki banyak pendukung parpol bisa memudahkan Presiden meloloskan berbagai kebijakan di DPR.
Meski begitu, harga dari kemudahan itu acap kali harus dibayar mahal. Tidak ada makan siang gratis. Secara alamiah, koalisi partai politik itu meminta balas jasa yang mereka berikan di parlemen. Salah satu transaksi yang paling lazim adalah jatah kursi menteri di kabinet yang dibentuk Presiden.
Dan Slater dari University of Michigan menggambarkan hal ini sebagai “kartelisasi” partai.
Kabinet Kerja saat ini, ada 16 menteri berlatar belakang parpol. Angka ini lebih sedikit dibanding 18 menteri yang tempati oleh profesional. Jika merujuk pada bertambahnya jumlah partai koalisi Jokowi saat ini, jumlah jatah menteri dari partai akan bertambah. Belum lagi parpol yang beru bergabung setelah capres Prabowo Subianto tidak terpulih.
Potensi bertambahnya menteri berlatar partai ini bisa mengancam menteri-menteri yang berasal dari profesional yang disukai Jokowi karena kinerjanya.
Namun bisa tereliminasi karena porsi 40:60 hingga 50:50 persen tersebut.
Hal ini bisa membuat kabinet tidak lagi berisi all president’s men, tetapi all political party’s men.
Jokowi misalnya memiliki sosok dari profesional seperti Menkeu Sri Mulyani, Rini Soemarno (Menteri BUMN), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), atau Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) di kabinetnya.
Bertambahnya partai yang harus menerima “kue” kekuasaan, bisa saja membuat kursi-kursi penting ini dikorbankan untuk memenuhi permintaan partai-partai tersebut.
Tidak Leluasa
Jika hal itu terjadi, Jokowi boleh jadi tidak lagi leluasa untuk menjalankan kebijakan sesuai visi misi atau janji-janji kampanye.
Porsi partai untuk menjalankan kebijakan bisa saja akan lebih besar seiring dengan bertambahnya kursi yang menjadi jatah mereka.
Berdasarkan kondisi tersebut, ada kemungkinan periode kedua Jokowi tidak lagi menggambarkan sebagai sosok paling berkuasa.
Berkumpulnya barisan parpol bisa saja menggeser kekuasaan dari Jokowi ke partai-partai tersebut. Dalam konteks ini, Jokowi seperti tersandera oleh “tirani” partai politik.
Partai-partai tersebut kemungkinan besar akan memaksimalkan berbagai keuntungan yang bisa diambil dari periode kedua Jokowi.
Kursi menteri yang mereka terima boleh jadi akan digunakan untuk meningkatkan posisi mereka sebagai partai politik untuk Pemilu 2024.
Jika merujuk pada pendapat Richard S Katz dan Peter Mair sebagaimana dikutip Marcus Mietzner, ada tiga hal yang akan dilakukan oleh partai politik saat terjadi hubungan antara negara dengan partai politik.
Banyaknya partai di kubu Jokowi bisa membuat dirinya tersandera.
Karena partai-partai tersebut akan mengejar regulasi yang menguntungkan mereka, misalnya membuat peraturan
yang membatasi munculnya partai-partai baru yang bisa mengancam eksistensinya.
Kedua, partai politik juga akan mencari keuntungan finansial. Katz dan Mair menyebut bahwa anggota “kartel” partai akan memaksa negara untuk memberikan subsidi secara finansial kepada mereka.
Katz dan Mair bahkan menyebut bahwa negara menjadi struktur yang mendukung partai tersebut. Subsidi ini dapat membantu sustainibilitas partai, sehingga mampu bertahan untuk Pemilu berikutnya.
Ketiga, mereka akan menguasai institusi kunci dalam negara. Langkah ini membuat partai-partai berkuasa menjadi partai bertipe dominan. Pada akhirnya, antara negara dan partai politik menjadi sesuatu yang sulit untuk dibedakan.
Ketiga hal ini bisa menguntungkan posisi partai menjelang Pemilu 2024, karena mendapatkan asupan sumber daya yang cukup memadai. Sebagai penguasa, mereka juga bisa mendominasi dan membuat regulasi yang melemahkan lawan mereka.
Oleh karena itu, strategi untuk menjadi presidentialized party boleh jadi akan menguntungkan mereka selama lima tahun periode kedua Jokowi.
Katz dan Mair terkadang mendeskripsikan hubungan antara negara dan partai seperti ini sebagai invasi partai terhadap negara.
Dalam konteks ini, Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara menjadi sosok yang terinvasi karena partai-partai yang mendapatkan keuntungan dari periode kedua Jokowi ini.
Idealnya, Jokowi bisa mengidentifikasi potensi masalah ini. Berbagai kebijakannya bisa jadi tidak terlaksana jika sosok-sosok profesional penting di kabinetnya harus berganti dengan kader partai.
Jika identifikasi tidak berhasil dilakukan, bukan tidak mungkin mulai tahun 2019, kepemimpinanya “tersandera” oleh partai koalisi.
*)Redaktur senior Detakpos