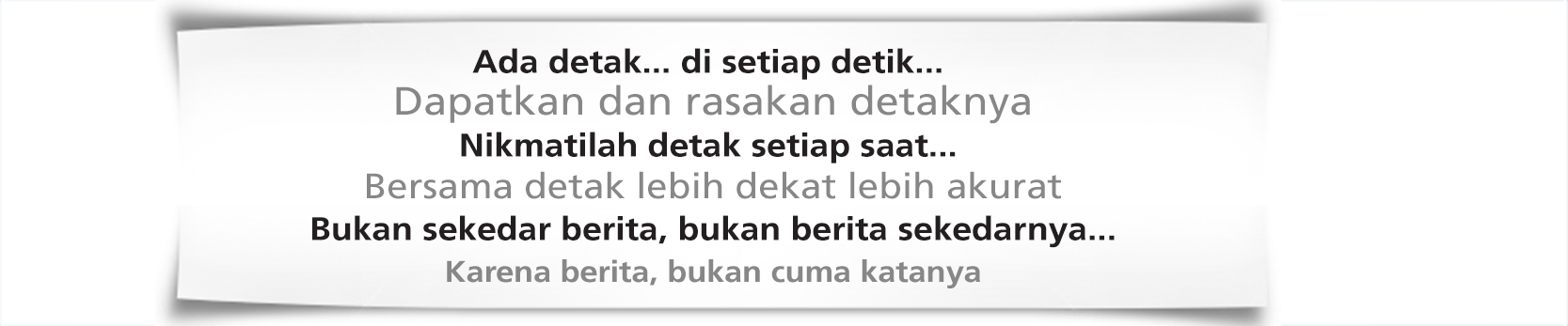Opini :Oleh H AAdib Hambali ,
PADA Hari Rabu, 31 Januari 2018, Nahdlatul Ulama (NU), berusia 92 tahun. Bersamaan Hari Lahir (Harlah) ini, selain memperingati sebagai rasa syukur dengan suka cita, perlu muhasabah apa yang masih menjadi pekerjaan rumah alias ”PR” bersama ke depan.
Jumlah warga NU atau yang mengaku Nahdliyin disebut-sebut mencapai 60 hingga 70 juta. Bahkan beberapa lembaga survei menyebut mencapai 90 juta hingga 120 juta orang. Ini suatu yang perlu disyukuri.
Sisi lain, besarnya jumlah Nahdliyyin ini menjadi daya tarik tersendiri bagi partai-partai politik. Tak ayal setiap kali ada pesta demokrasi seperti pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah mereka menjadi incaran.
Nahdliyyin pun ditarik ke sana-kemari oleh kepentingan politik untuk mendongkrak suara, sehingga klaim-klaim dari para politisi itu muncul bersamaan membesarnya ”libido” politik Nahdliyyin sendiri.
NU lahir pada 31 Januari 1926 sebagai jam’iyah diniyah ijtimaiyah (organisasi sosial keagamaan). Namun garis perjuangan NU sebagai ormas sosial keagamaan mengalami perubahan ketika masuk ke ranah politik, terutama setelah ada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, untuk melawan kembalinya penjajah Belanda dan sekutu.
Setelah itu minat politik NU menguat ketika ormas Masyumi berubah menjadi partai politik. NU dan Muhammadiyah menjadi pendukung Masyumi, kemudian menjadi partai politik terbesar di hingga era 1950-an.
Dari berbagai literatur yang dihimpun menyebutkan, perebutan kekuasaan di Masyumi kemudian menyebabkan NU berpisah dan menjadi partai politik sendiri pada 1952.
NU berubah menjadi partai politik. Tujuan itu antara lain untuk penyaluran dana bagi warga NU termasuk fasilitas pendidikan dan keagamaan, peluang bisnis bagi warga NU, dan posisi birokrasi bagi anggota NU. (Pengamat NU Greg Fealy).
Kenyataanya, menjadi Partai NU hanya menguntungkan elite-elite-nya. Kemudian setelah Pemilu 1955, muncul wacana kembali ke Khittah NU 1926, yaitu sebagai ormas sosial keagamaan.
Selama bertahun-tahun wacana kembali ke Khittah NU gencar disuarakan kaum muda. Akhirnya Partai NU di-fusi-kan Pemerintah Soeharto pada 1973, bersama sejumlah partai Islam digabung ke dalam PPP.
Tokoh-tokoh NU pun beralih organisasi politik ke PPP. Campur tangan politik di tubuh NU berlangsung hingga tahun 1980-an.
Banyak pengurus NU, pemimpin pondok pesantren, merangkap menjadi pengurus PPP. Akibatnya organisasi NU tidak terurus dengan baik.
Desakan kembali ke khittah 1926 semakin menguat hingga NU lepas dari partai politik melalui keputusan Muktamar NU di Situbondo pada 1984.
Dalam muktamar itu disepakati Khittah NU, yang isinya, organisasi NU tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun.
Karena itu, hak politik setiap Nahdliyin tetap dilindungi undang-undang. NU meneguhkan agar penggunaan hak-hak politik dilakukan secara bertanggung jawab, demokratis, konstitusional, taat hukum dan menjunjung mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan masalah.
Setiap Nahdliyyin adalah warga Negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.Istilah populernya, ”NU tidak kemana-mana, warga NU ada di mana-mana. Para tokoh NU menyebar ke banyak partai.”
Karena politisi warga NU berusaha menyeret organisasi ini untuk kepentingan politik praktis, sering muncul kritik terkait konsistensi dalam menjalankan Khittah NU.
Hal itu diperuncing oleh ”perselingkuhan” elite NU dengan parpol dari pusat hingga daerah menjelang Pilkada 2018, Pemilu dan Pilpres 2019.Wallohu A’lam.
*Pemerhati politik dan redaktur di Bojonegoro.