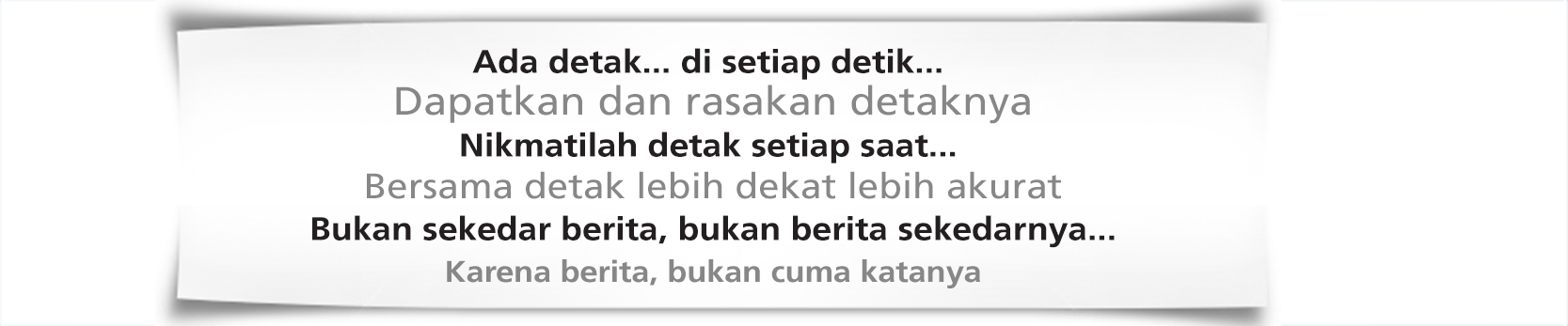Opini Oleh H AAdib Hambali.(*)
”MAHAR” atau politik uang menjadi trend menjelang Pilkada 2018. Sebetulnya istilah ini sudah lama muncul, namun belum ada yang terang-terangan mengakui.
Adalah kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti yang menugngkap ihwal mahar politik Rp 40 miliar sebagai syarat dirinya untuk mendapat rekomendasi bakal calon gubernur Jawa Timur.
La Nyalla mengaku ditanya kesanggupan dirinya menyediakan dana Rp 40 miliar. Dalihnya untuk membayar saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS), saat coblosan pilkada.
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Jika dana tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dia tidak akan mendapatkan rekomendasi.La Nyalla tidak bersedia memenuhi permintaan itu sehingga tidak memperoleh rekomendasi.
Namun Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono meluruskan, bahwa La Nyala menyerahkan surat tugas ke DPP karena PAN tidak bersedia diajak koalisi sehingga tidak memenuhi kuota kursi yang disyaratkan bisa mengusung calon gubernur di Pilkada Jatim, bukan karena mahar.
Kasus mahar pilkada juga muncul di Cirebon. Mantan Kapolresta Cirebon Brigjen (Purn) Siswandi merasa kecewa terhadap DPD PKS Kota Cirebon. Padahal, sudah ada komitmen koalisi Gerindra dan PAN. Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS pada detik-detik akhir pendaftaran. Namun, dia dan timnya enggan memberikan mahar politik, sehingga tidak diberi rekomendasi. Pjs Ketua DPW PKS Jabar Nur Supriyanto membantah pernyataan Siswandi.
Ibarat gunung es, La Nyalla dan Siswandi hanya yang muncul di permukaan, sehingga perlu ditelusuri kebenarannya agar praktik politik uang di balik Pilkada serentak 2018 bisa terbongkar.
Sebab mahar dalam pilkada dinilai bisa menjadi embrio praktik korupsi yang selama ini menjerat sejumlah kepala daerah.Bawaslu berjanji terus menyuarakan gerakan memerangi politik uang dalam pilkada karena ingin mencegah bahaya laten korupsi.
Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, antara lain karena alasan untuk mengembalikan uang yang begitu banyak dikeluarkan saat pilkada.Uang yang begitu banyak itu harus keluar, karena ada transaksi, ada politik uang untuk mendapat dukungan, atau mahar. (Ketua Bawaslu Pusat Abhan.SM/15/2018).
Perlu juga diteliti tentang fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak. Pasalnya, bisa jadi calon tunggal muncul karena ada ”borong dukungan” seluruh parpol di daerah tersebut.
Parpol juga bersikap pragmatis, tidak mau susah payah mencalonkan kadernya. Borong dukungan seperti ini jelas menimbulkan high cost politik (biaya politik yang tinggi).Itu berpotensi dibayar saat menjabat, dan ini bisa menimbulkan praktik korupsi oleh kepala daerah..Praktik mahar bisa merusak proses yang demokratis.
Efek merusaknya, bisa membuat dukungan kepada tokoh ditentukan oleh uang mahar, bukan karena calon itu orang yang bagus, yang mumpuni. Sementara, ada tokoh yang bagus tidak mendapat dukungan karena tidak mampu membayar mahar.Hal yang juga menjadi kekhawatiran adalah minimnya adu program dan menguatnya politik identitas dalam pilkada.Terlebih lagi dengan fenomena pasangan calon tunggal di berbagai daerah, yang membuat pemilih tidak memiliki alternatif pilihan.
Kekhawatiran mahar menjadi embrio korupsi itu sangat beralasan. Terbukti Kementerian Dalam Negeri tahun lalu mencatat sebanyak 77 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT), dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka terjerat korupsi karena masuk di daerah rawan, seperti suap, bermain proyek, manipulasi anggaran, memeras sampai penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Dan hampir semua oknum kader partai politik.
Mahar dan politik balasbudi ini dua hal berbeda tapi punya damage yang mungkin sama untuk demokrasi di IndonesiaDemokrasi di Indonesia pasti membutuhkan biaya tinggi. Namanya juga sering juga disebut pesta demokrasi.Pesta tidak ada yang tidak membutuhkan uang.
Bila si kandidat mempunyai tingkat keterpilihan tinggi, biasanya akan dilamar parpol. Tetapi parpol perlu biaya, jadilah parpol mencari sponsor untuk kampanye. Kalau menang, politik balas budi yang digunakan, kalau kalah dianggap judi politik.Kalau tingkat keterpilihan rendah mesti membeli kendaraan politik, agar bisa maju sebagai calon.
Sistem ideal sudah ada di negara ini, yaitu negara membiayai parpol, parpol melahirkan pemimpin politik untuk menjadi eksekutif di semua level.
Yang paling mungkin untuk menjadi pemimpin di Indonesia baik bupati, wali kota, gubernur atau presiden minimal harus punya satu kriteria. Meminjam istilah pengamat Hebdri Satrio, di antara kaya banget (sangat), ngetop banget atau pinter banget.
Pertanyaannya, apakah mahar politik dan politik balas budi bisa diberantas dari sistem demokrasi? Bisa, tapi tidak dalam waktu dekat.
*Pemerhati politik dan redaktur senior di Bojonegoro